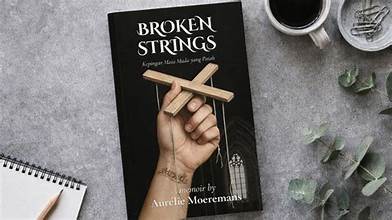Institusi pendidikan, tak terkecuali madrasah, seringkali menjadi cermin tempat norma-norma sosial. Termasuk konsep tentang kesetaraan gender terinternalisasi kepada siswa sebagai bagian norma yang oleh otoritas pendidikan bentuk. Sebuah fenomena observasional yang menarik muncul dari pola kerja sama siswa dalam tugas logistik MBG. Makudnya, mengacu pada kegiatan pemindahan benda untuk kepentingan bersama.
Peristiwa itu menunjukkan adanya kontras perilaku mencolok alih-alih dinamika mereka di kelompok belajar akademik. Menariknya, dalam konteks pemindahan MBG, pola kerja sama fungsional yang melampaui batas gender dapat terwujud.
Namun, ketika berhadapan dengan tugas akademik, kesetaraan itu seolah runtuh. Tergantikan oleh peran gender yang tidak setara antara siswa laki-laki dan perempuan. Di mana siswa perempuan menunjukkan inisiatif, tanggung jawab, dan hasil kerja yang jauh lebih dominan. Sedangkan sebaliknya, siswa laki-laki cenderung pasif dan tidak menunjukkan tanggung jawab yang setara dengan siswa laki-laki.
Kerja Sama Fungsional
Oleh karena itu, esai ini bertujuan menganalisis disparitas perilaku menggunakan lensa teori sosial. Khususnya Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) dan Teori Peran Gender (Gender Role Theory). Tak lain untuk memahami akar sosiologis mengapa kesetaraan yang tampak dalam proses pengambilan dan pengembalian MBG dapat menghilang di ruang kelas.
Ambil contoh pola kerja sama dalam tugas logistik MBG di madrasah. Siswa laki-laki bertugas mengambil wadah penuh yang berat (sekitar 24 keranjang). Sementara siswa perempuan mengembalikan wadah kosong yang jauh lebih ringan (8–12 keranjang). Pola kerja sama ini terbentuk karena rata-rata jumlah siswa adalah di rentang 32-36. Dengan medan pengambilan maupun pengembalian mengharuskan siswa naik turun tangga ada yang di lantai 2 dan 3.
Selain itu, dengan siswa laki-laki membawa keranjang berjumlah 24 dengan medan tersebut di menujukkan sisi maskulinitsnya. Namun, keranjang tersebut hanya muat untuk 24 MBG masih tersisa 8-12 siswa, sehingga mereka tetap membutuhkan bantuan untuk memudahkan tugas mereka. Hal ini menujukkan bahwa maskulinitas (kekuatan) siswa laki-laki tetap membutuhkan feminitas perempuan agar tujuan MBG sampai ke kelas dan ternikmati bersama.
Utilitas Kolektif
Pola ini menunjukkan kesepakatan fungsional yang tinggi, di mana distribusi beban berdasar pada proporsionalitas kemampuan fisik rata-rata yang terakui bersama. Fenomena ini paling efektif tergambarkan melalui kerangka Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory).
“Upaya mendorong kesetaraan tidak cukup hanya dengan menyatukan siswa dalam satu kelompok. Perlu intervensi pedagogis eksplisit untuk membongkar peran gender yang terinternalisasi, merancang ulang insentif, dan mendefinisikan kembali akuntabilitas kelompok secara tegas.”
Teori ini berargumen bahwa individu bertindak sebagai agen rasional yang melakukan kalkulasi untung-rugi untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, “keuntungan pribadi” tersebut adalah terpenuhinya tujuan kolektif yakni, akses segera terhadap makanan yang merupakan kebutuhan mendesak atau primitif.
Kerja sama fungsional ini terwujud karena dua alasan kuat. Pertama, tujuan jelas dan sesaat (utilitas tinggi); hasil kerja sama (MBG terangkut dan makanan tersedia) bersifat konkret, terukur, dan memiliki manfaat langsung bagi semua pihak, sehingga insentif untuk kerja sama menjadi sangat kuat. Dan, kedua, efisiensi sebagai rasionalitas; pembagian kerja yang berdasar pada kekuatan fisik menjadi pilihan paling rasional dan efisien untuk mencapai tujuan bersama dengan upaya kolektif minimum. Di sini, peran gender terkesampingkan sepenuhnya demi utilitas kolektif.
Hal ini membuktikan bahwa ketika insentif berupa pemenuhan kebutuhan dasar atau keuntungan yang jelas dan langsung berada di depan mata, manusia akan mengaktifkan mekanisme adaptasi dan negosiasi, melampaui norma sosial yang kaku demi mencapai kata sepakat. Kerja sama semacam ini bersifat transaksional dan terdorong oleh insting dasar akan kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan.
Reproduksi Peran Gender
Kontras yang mencolok terjadi justru di ruang kelas, kontras yang menghadirkan dilema pedagogis. Ketika siswa laki-laki dan perempuan bersatu dalam satu kelompok akademik, inisiatif, tanggung jawab, dan penyelesaian tugas (bahkan hingga tahap presentasi) cenderung terdominasi siswa perempuan. Ironisnya, siswa laki-laki seringkali hanya menunjukkan partisipasi pasif, sekadar berkontribusi karena terdorong rasa takut guru memarahinya, bukan karena dorongan intrinsik untuk mencapai tujuan akademik.
Fenomena ini paling tepat teranalisis melalui Teori Peran Gender (Gender Role Theory) yang terkuatkan oleh lensa konstruksi sosial (social constructivism). Di mana peran gender adalah serangkaian harapan normatif mengenai bagaimana individu harus bersikap berdasarkan jenis kelamin mereka dalam suatu budaya. Di banyak masyarakat, stereotipe menghubungkan perempuan dengan ketelitian, tanggung jawab non-agresif, dan peran expressive (berorientasi pada pemeliharaan hubungan). Sementara laki-laki terhubungkan dengan peran instrumental yang seringkali tersalahartikan menjadi keengganan terhadap pekerjaan detail.
Dalam konteks akademik, disparitas ini muncul karena beberapa faktor; pertama, manfaat jangka panjang yang abstrak. Di mana keuntungan akademik (nilai atau pengetahuan) bersifat abstrak, sehingga insentifnya lebih lemah daripada kebutuhan primer. Kelemahan insentif ini membuka jalan bagi norma sosial yang terinternalisasi untuk mengambil alih.
Reproduksi norma sosial juga berperan; tanpa insentif yang kuat, siswa kembali ke pola perilaku yang mereka pelajari dari lingkungan sosial. Siswa perempuan memikul peran caregiver atau pengemban tanggung jawab detail. Sementara siswa laki-laki memanfaatkan peran pasif mereka, sebuah pola yang menunjukkan reproduksi habitussosial di ruang kelas.
Kedua, lemahnya faktor internal, yakni motivasi diri karena mengganggap sekolah sebagai sesuatu yang menghabiskan waktu. Terlebih dengan adanya narasi di media sosial yang menyatakan jika sekolah scam ataupun romantisasi kesuksesan orang yang tidak maupun putus sekolah. Hal itu menyebabkan partisipasi pasif siswa laki-laki hanya terdorong oleh rasa takut akan otoritas guru (motivasi eksternal). Bukan berlandaa tanggung jawab intrinsik, berbanding terbalik dengan kerja keras siswa perempuan yang terdorong oleh rasa tanggung jawab (internal).
Reinternalisasi Cara Pandang
Disparitas antara dua pola perilaku ini, yakni efisiensi rasional dalam kerja fisik versus stagnasi peran gender dalam kerja kognitif menggarisbawahi tesis kunci. Ialah, kesetaraan gender di madrasah hanya dapat terwujud secara fungsional dan adil ketika ada tujuan bersama yang bersifat primitif, jelas, dan menguntungkan pribadi secara langsung. Dalam situasi seperti pemindahan MBG, struktur gender menjadi cair karena adanya utilitas bersama yang kuat.
Sebaliknya, di lingkungan akademik yang terdorong tujuan yang lebih abstrak dan jangka panjang, norma-norma sosial dan peran gender yang kaku kembali mendominasi. Ini menjadi pengingat pahit bahwa meskipun siswa telah mencapai kesepakatan rasional kerja fisik, mereka belum mencapai kesetaraan sosial yang sesungguhnya dalam ranah kognitif dan tanggung jawab. Implikasinya bagi pendidikan sangat mendalam.
Upaya mendorong kesetaraan tidak cukup hanya dengan menyatukan siswa dalam satu kelompok. Perlu intervensi pedagogis eksplisit untuk membongkar peran gender yang terinternalisasi, merancang ulang insentif, dan mendefinisikan kembali akuntabilitas kelompok secara tegas. Hanya dengan cara itu, motivasi siswa laki-laki dapat beralih dari sekadar menghindari hukuman menjadi tanggung jawab aktif dan kolaboratif. Memastikan kesetaraan bukan hanya tentang berbagi beban fisik, tetapi juga berbagi beban kognitif untuk masa depan bersama.[]