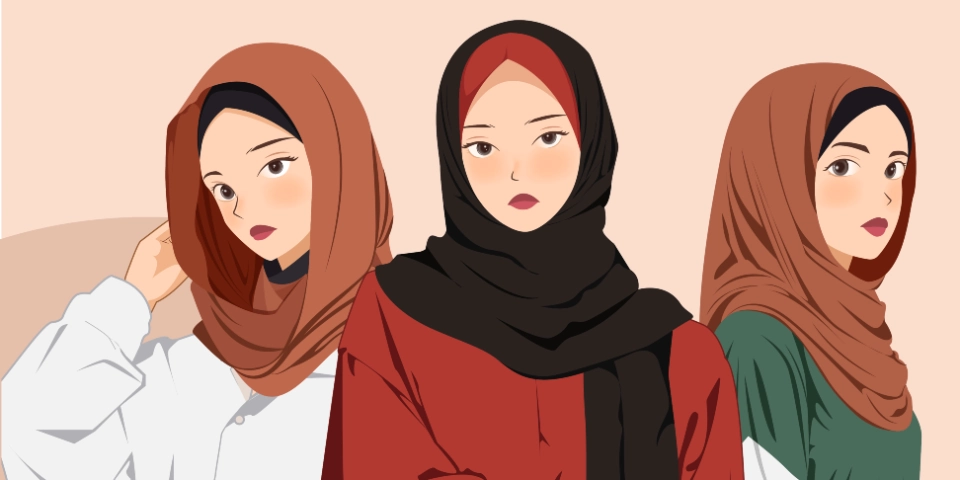Standar kecantikan bukanlah hukum alam; ia adalah sebuah mata uang sosial, nilainya tertentukan oleh pasar budaya dan algoritma yang terus berubah. Hari ini, pasar tersebut terdominasi sebuah mekanisme kerja dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah ada sebelumnya: media sosial.
Jika dahulu standar kecantikan teratur oleh majalah dan iklan cetak, kini ia terorkestrasi oleh layar yang kita pegang. Tersaring melalui filter, dan terkuatkan oleh like serta validasi digital. Konstruksi visual inilah yang secara efektif telah mengambil alih peran sebagai regulator global. Lantas menciptakan ekspektasi yang semakin seragam, tapi ironisnya, semakin sulit terjangkau.
Fenomena ini berfokus pada peran media sosial sebagai arsitek tunggal standar kecantikan kontemporer. Instagram dan TikTok adalah platform yang tidak hanya mengikuti tren tetapi juga membuatnya. Platform ini menggunakan algoritma yang cermat untuk memprioritaskan dan mempromosikan citra gaya hidup, bentuk wajah, dan tubuh tertentu yang terbukti memiliki tingkat interaksi tertinggi.
Gelembung Visual
Hal ini secara efektif menghasilkan gelembung visual, di mana kita berulang kali terhadapkan pada prototipe kulit “ideal” yang tidak memiliki pori, perut rata, dan simetri wajah sempurna. Ini adalah hasil dari kombinasi intervensi kosmetik, genetik, dan, yang paling penting, manipulasi digital. Miliaran pengguna terpaksa untuk mengukur diri mereka terhadap sebuah patokan, yang secara harfiah tidak nyata, karena cita-cita ini menjadi acuan universal yang melampaui perbedaan etnis dan geografis.
Standarisasi digital ini memiliki efek yang paling signifikan pada kesehatan mental dan identitas diri generasi muda, terutama mahasiswa dan remaja. Mereka adalah penduduk asli dunia digital yang hidup dalam budaya perbandingan yang tidak pernah berhenti. Generasi ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang membandingkan diri dengan selebritas yang jauh. Sebaliknya, mereka membandingkan diri dengan rekan sebaya, influencer, atau bahkan diri mereka sendiri dalam bentuk digital. Sebuah fenomena yang mendapat sebutan “kesenjangan kecantikan digital” tersebabkan oleh perbandingan terus menerus ini.
Ketika realitas fisik seseorang jauh dari kesempurnaan virtual yang terunggah ke feed, hal itu menghasilkan self-criticism yang akut. Yang sering bermanifestasi sebagai dismorfia citra tubuh (body image dysmorphia) yang ringan hingga parah. Kepercayaan diri menjadi terikat pada metrik eksternal, berapa banyak like yang tertkumpulkan, seberapa “sempurna” foto yang berhasil terunggah. Nilai diri tereduksi menjadi estetika visual, mengubah tubuh dari wadah pengalaman menjadi sekadar objek yang estetika.
Agenda Diskriminatif
Lebih jauh, standarisasi kecantikan melalui medsos membawa agenda diskriminasi yang terselubung. Algoritma cenderung beroperasi berdasarkan data historis tentang apa yang “populer,” dan sering kali, popularitas tersebut berakar pada bias rasial dan kelas sosial. Secara global, dominasi citra Barat (kulit cerah, fitur wajah tertentu) masih menjadi arus utama.
Hal ini menciptakan kolonialisme estetika digital, di mana perempuan dari berbagai etnis merasa terdorong untuk memodifikasi penampilan alami mereka. Baik melalui filter, aplikasi pengeditan, atau bahkan prosedur kosmetik, hanya agar sesuai dengan standar yang teranggap “menarik” oleh sistem algoritma. Keragaman tubuh, warna kulit, dan tekstur rambut yang seharusnya menjadi kekayaan visual manusia justru terpinggirkan. Teranggap sebagai “ketidaksempurnaan” yang harus mendapat perbaikan sebelum tertampilkan ke publik digital.
Eksistensi self-censorship adalah hasil jangka panjang dari dominasi ini. Generasi muda belajar untuk menghindari menampilkan sisi diri mereka yang teranggap “tidak fotogenik” atau “tidak ideal”. Mereka menyensor jerawat, menghindari memposting foto dengan berat badan “berlebihan”, dan bahkan membatasi pengalaman hidup mereka karena khawatir mereka tidak akan “terlihat bagus” di kamera.
Identitas dan Persona
Persona yang terpoles dan terekayasa menggantikan ekspresi diri asli. Hal ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang terlihat dari luar, tetapi juga menghambat identitas asli seseorang. Identitas asli seseorang sekarang berjuang untuk berkembang di bawah bayang-bayang ekspektasi visual yang mengerikan.
Melihat kondisi yang semakin mengglobal dan merusak ini, perlawanan harus datang dari kesadaran kritis digital. Mahasiswa dan aktivis digital memiliki peran utama untuk mendekonstruksi narasi kecantikan yang seragam ini. Upaya perlawanan tidak terletak pada penolakan perawatan diri, sebab merawat diri adalah hak otonom. Namun, pada pemisahan nilai diri (self-worth) dari penilaian eksternal.
Kampanye body neutrality dan self-acceptance harus mendapat dorongan bukan sekadar sebagai tren, tetapi sebagai filosofi hidup. Generasi muda perlu terlatih untuk menjadi pengguna medsos yang cerdas, yang dapat mengidentifikasi dan menolak manipulasi visual. Kita harus menuntut transparansi dari platform tentang bagaimana algoritma mereka mempromosikan citra, dan secara aktif mempromosikan konten yang merayakan keberagaman yang nyata.
Pada akhirnya, peperangan melawan standar kecantikan yang teratur dunia adalah peperangan untuk membebaskan tubuh dan pikiran. Dunia mungkin akan terus mencoba mengatur definisi kecantikan, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk mengkritisi, menolak, dan menulis ulang definisinya sendiri. Kecantikan yang autentik tidak akan pernah menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, melainkan sesuatu yang sudah melekat: keberagaman, keunikan, dan kontribusi personal seseorang kepada dunia. Ketika nilai seseorang diukur bukan dari penampilannya, melainkan dari kedalaman karakternya, kita akan mencapai kebebasan yang lebih otentik dari tirani estetika digital.[]