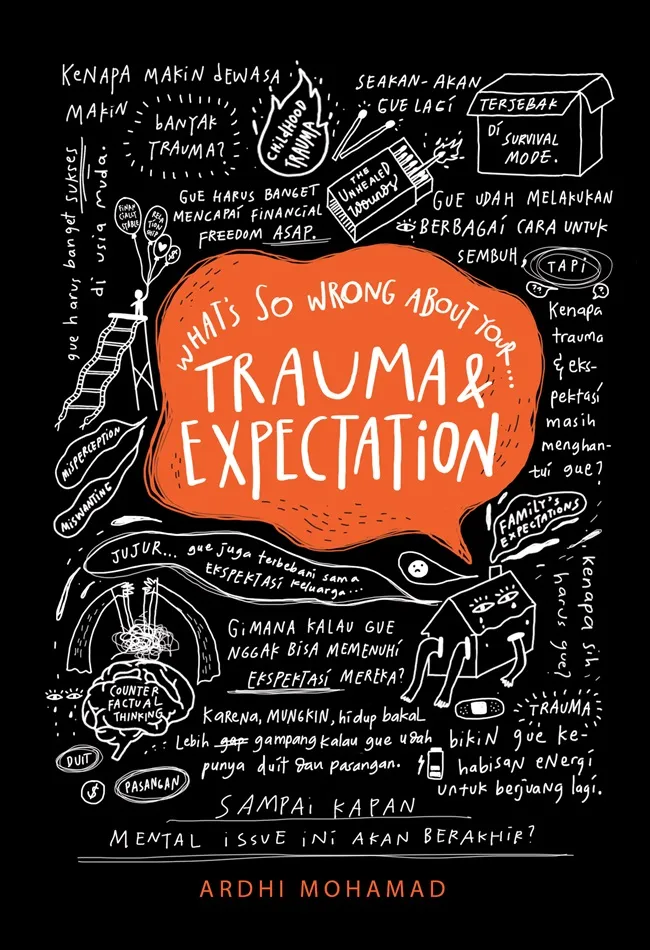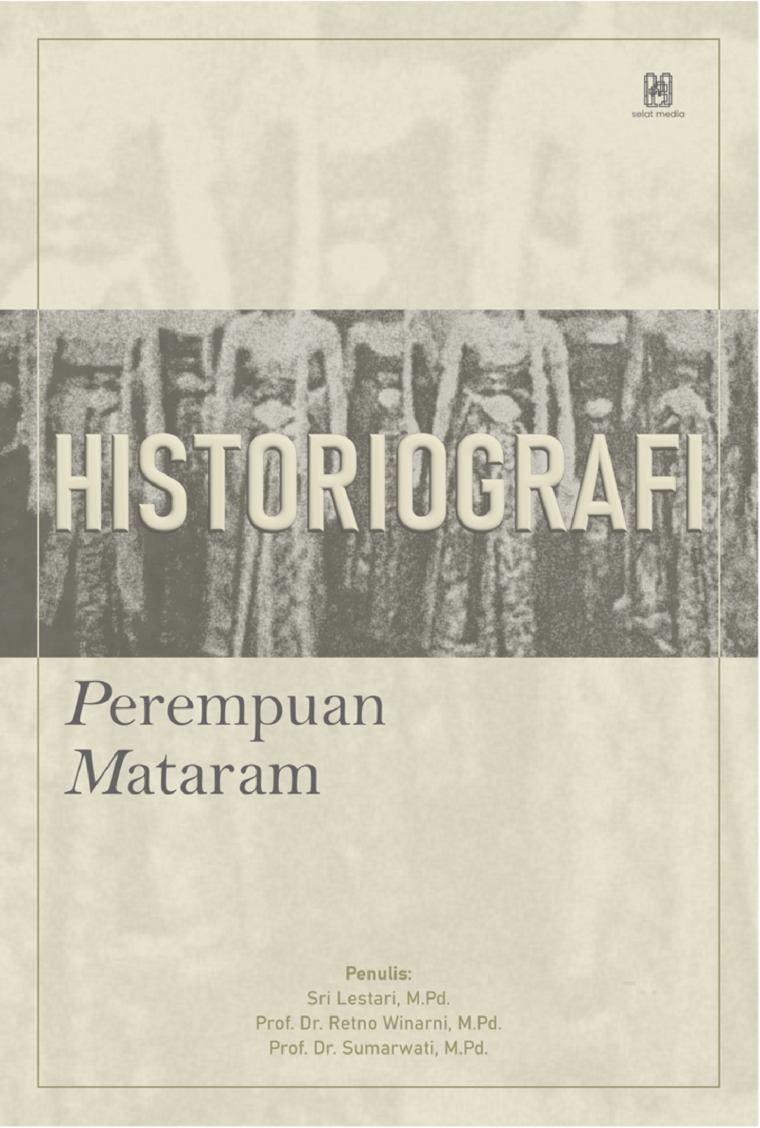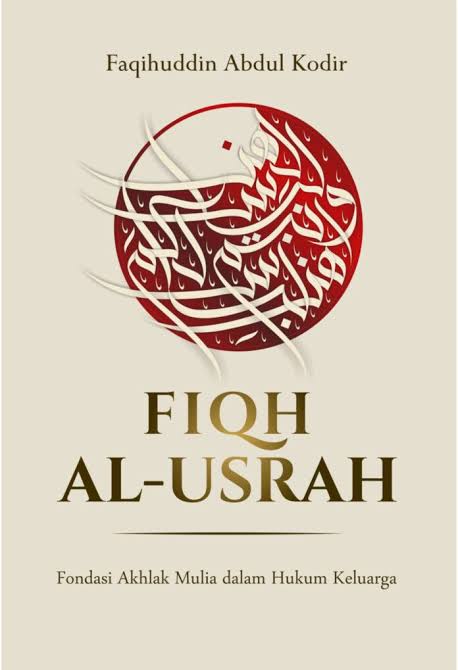Pernahkah Anda merasa lelah luar biasa, padahal secara fisik Anda tidak sedang melakukan aktivitas berat? Rasa lelah itu sering bukan berasal dari otot yang bekerja terlalu keras, melainkan dari pikiran yang tak henti mengejar standar kesempurnaan. Dalam buku fenomenal What’s So Wrong About Your Trauma & Expectation (2024) karya Ardhi Mohamad, Esther Lubis mengajak kita menyelami sebuah realitas pahit: bahwa banyak dari ekspektasi tinggi yang kita pikul hari ini sebenarnya adalah “perisai” yang kita bangun untuk menutupi luka masa lalu yang belum pulih. Menulis tulisan tentang buku ini bukan sekadar merangkum isi. Melainkan sebuah upaya melakukan rekonstruksi diri di sebuah proses merombak ulang struktur berpikir agar tidak lagi dihantui oleh rasa takut.
Fenomena krisis kesehatan mental modern, seperti burnout, imposter syndrome, dan low self-esteem, sering kali berasal pada satu hal: beban ekspektasi yang menyesakkan. Kita hidup dalam era di mana pencapaian selalu dipamerkan secara instan. Dengan begitu, tanpa sadar kita menciptakan standar yang mustahil untuk dicapai setiap hari. Namun, melalui pendekatan psikologi popular yang hangat, Esther Lubis menyikapi bahwa obsesi kita terhadap kesempurnaan sering kali merupakan manifestasi dari trauma masa lalu yang belum tuntas diolah.
Trauma tersebut tidak selalu berupa kejadian tragis yang besar; bisa jadi itu adalah pola asuh yang menuntut prestasi tanpa henti, lingkungan sekolah yang penuh perundungan, atau momen di mana kita merasa tidak berharga jika tidak menjadi yang terbaik. Inilah alasan mengapa rekonstruksi diri menjadi sangat penting. Kita perlu membongkar alasan di balik ambisi kita selama ini: apakah kita mengejar sesuatu karena mencintainya, atau karena kita takut jika kita “biasa saja”, kita tidak akan layak untuk dicintai?
Hubungan Kausalitas
Untuk memahami keterkaitan ini, kita perlu menggunakan metode analisis yang jujur dan reflektif. Inti dari pemikiran ini adalah memahami hubungan kausalitas: Trauma menciptakan rasa tidak aman, dan rasa tidak aman menciptakan ekspektasi. Ekspektasi tinggi yang kita ciptakan adalah cara otak memberikan rasa aman palsu. Kita berpikir, “Jika aku sukses, tidak ada yang bisa meremehkanku lagi,” atau “Jika aku menyenangkan semua orang, tidak ada yang akan meninggalkanku.”
Sebagaimana kutipan kuat dalam buku tersebut: “Ekspektasi tinggi yang kamu ciptakan sering kali adalah cara anak kecil di dalam dirimu berteriak agar tidak lagi disepelekan seperti dulu.” Kutipan ini menjadi kesadaran bagi banyak pembaca bahwa selama ini mereka sedang menjalankan “misi penyelamatan” untuk diri mereka di masa kecil (inner child), namun dengan cara yang justru menyiksa diri mereka di masa dewasa.
Rekonstruksi diri tidak akan terjadi tanpa tindakan nyata. Langkah pertama adalah membangun kesadaran penuh (mindfulness). Kita harus belajar menjeda setiap kali rasa cemas muncul akibat ekspektasi. Tanyakan pada diri sendiri: “Siapa yang sebenarnya menginginkan hal ini? Apakah ini keinginan tulusku, atau aku hanya takut mengecewakan orang lain?”
Secara nyata, Esther Lubis mendorong kita untuk berani menetapkan batasan (boundaries). Bagi banyak orang, menetapkan batasan adalah hal yang menakutkan karena adanya trauma penolakan. Namun, kita harus belajar berkata “tidak” pada tuntutan luar yang menguras energi mental tanpa merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar untuk membela diri. Kita perlu memahami kutipan penting lainnya: “Kamu tidak bertanggung jawab atas kekecewaan orang lain terhadap keputusan yang kamu ambil untuk kesehatan mentalmu sendiri.”
Refleksi Akhir
Selanjutnya, langkah praktis lainnya adalah melakukan dialog dengan inner child. Alih-alih memarahi diri sendiri saat gagal, cobalah untuk memvalidasi rasa sedih itu. Katakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk tidak menjadi luar biasa setiap saat. Dengan secara sadar menurunkan standar perfeksionis yang mencekik, kita memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan menyadari bahwa harga diri kita bersifat permanen dan ia tidak berkurang hanya karena produktivitas kita menurun.
Sebagai refleksi akhir, penting untuk dipahami bahwa pemulihan (healing) bukanlah sebuah garis lurus menuju kesempurnaan. Sering kali, kita merasa sudah membaik, namun di hari berikutnya trauma itu muncul kembali. Itu adalah hal yang manusiawi. Penyembuhan yang sejati bukanlah tentang menjadi orang baru yang tanpa cela, melainkan tentang keberanian untuk meruntuhkan tembok pertahanan yang dulu kita bangun di atas rasa sakit, lalu menggantinya dengan kasih sayang pada diri sendiri.
Rekonstruksi diri menuntut kita untuk berhenti memusuhi masa lalu. Kita harus berhenti menyalahkan diri kita yang dulu pernah hancur atau tidak berdaya. Sebaliknya, kita harus mulai menerima bahwa segala ketidaksempurnaan adalah bagian dari cerita hidup yang utuh. Kita tidak lagi berlari mengejar validasi dunia untuk menutupi lubang di hati. Melainkan belajar mengisi lubang itu dengan penerimaan diri yang tulus.
Pada akhirnya, esensi dari setiap bab dalam buku Trauma & Expectation bermuara pada satu kebenaran yang membebaskan. “Penyembuhan bukan tentang menjadi orang baru, tapi tentang memaafkan diri kita yang dulu yang pernah hancur”. Di titik itulah, kita akhirnya benar-benar bebas. Kita tidak lagi menjadi tawanan masa lalu maupun budak ekspektasi masa depan. Kita belajar hidup di sini, saat ini, dengan segala luka yang telah mengering dan menjadi kekuatan baru.[]