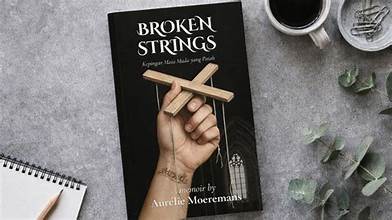Di era digital seperti saat ini, media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang, terutama generasi muda. Sayangnya, bersamaan dengan kemudahan berinteraksi, muncul pula bentuk-bentuk kekerasan baru yang tak kalah berbahayanya alih-alih kekerasan fisik. Salah satunya adalah cyber bullying atau perundungan secara daring, yang dampaknya seringkali orang meremehkannya. Di Indonesia, fenomena ini semakin memprihatinkan, terutama jika kita menyasar kelompok yang paling rentan yaitu perempuan.
Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) terus meningkat. Pada tahun 2022 tercatat terdapat 1.721 kasus KSBG, dan naik tajam hingga 83% alih-alih tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut terdiri dari bermacam-macam bentuk seperti penyebaran konten pribadi tanpa izin, hinaan seksual di kolom komentar, hingga pemerasan dengan menggunakan foto korban. Di balik angka-angka ini, ada perempuan-perempuan yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan tekanan psikologis yang berkepanjangan.
Ketimpangan Norma
Masalah ini tidak hanya terjadi dalam ruang hampa melainkan dunia maya. Walau bersifat virtual, tapi tetap mencerminkan norma dan ketimpangan yang ada di dalam dunia nyata. Dalam masyarakat patriarkal seperti Indonesia, perempuan seringkali menjadi objek penilaian berdasarkan penampilan, tutur kata, dan gaya hidupnya. Ketika perempuan berusaha menyuarakan opini, mengunggah foto diri, ataupun tampil percaya diri di media sosial, mereka justru menerima komentar negatif yang merendahkan.
Ujaran seperti “modal filter” seakan-akan perempuan tak boleh percaya diri. Ataupun “mending balik ke dapur” seakan-akan perempuan hanya layak berada di ranah domestik menjadi bentuk perundungan yang teranggap biasa, tetapi sejatinya membentuk pola kekerasan psikologis yang berulang.
Perempuan menjadi target empuk karena adanya standar ganda di masyarakat. Orang menghargai mereka karena kecantikan, tetapi mendapat kritik jika teranggap terlalu menunjukkan diri. Mereka mendapat pujian saat tampil anggun, tapi orang benci ketika bersuara tegas. Hal inilah yang membuat mereka lebih rentan terhadap bentuk-bentuk cyberbullying yang menyerang karakter personal.
Tak sedikit pula pelaku cyberbullying datang dari sesama perempuan, menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekadar tentang gender, tapi juga tentang pola pikir kolektif yang terbentuk dari konstruksi sosial yang menindas. Rasa iri, tekanan sosial, atau norma kecantikan yang sempit membuat sebagian orang merasa berhak mengomentari tubuh dan hidup orang lain tanpa empati.
Kikisan Realita
Kasus yang mencerminkan realitas ini terjadi pada Em Ford, seorang beauty influencer asal Inggris yang memutuskan untuk memposting fotonya tanpa riasan wajah. Hasilnya, ia menuai ribuan komentar kejam seperti “kamu menjijikkan”, “tutup wajahmu”, atau “wajahmu menakutkan”. Ketika ia merespons dengan merias wajah, komentar yang datang pun tak kalah merendahkan, seperti “terlalu palsu”, “kamu membohongi orang lain”.
Pengalaman ini ia tuangkan dalam video viral berjudul You Look Disgusting, yang memperlihatkan betapa inkonsistensi penilaian publik terhadap perempuan. Apapun yang mereka lakukan, mereka tetap menjadi sasaran. Video ini menjadi simbol penting bahwa cyberbullying tidak hanya melukai secara emosional, tapi juga mempermalukan dan mengikis harga diri perempuan.
Realita serupa terjadi pula di Indonesia, meski mungkin tidak selalu terdokumentasi secara publik. Namun berdasarkan studi yang oleh Fariha Mumu dan Ahsan Abdullah lakukan berjudul “Impact of Cyberbullying on Mental Health of Women: A Study of University Students in Dhaka City” menunjukkan bahwa 77% perempuan usia mahasiswa pernah mengalami cyberbullying. Dampaknya serius, seperti 25% mengalami depresi, 24% kehilangan rasa percaya diri, dan 20% mengalami trauma sosial. Ironisnya, sebagian besar korban memilih diam. Hanya sekitar 11% dari mereka yang berani mencari bantuan profesional, sisanya menanggung luka secara senyap-senyap.
Fenomena ini menunjukkan bahwa perundungan daring terhadap perempuan bukanlah hanya masalah teknis semata, melainkan persoalan struktural yang bersumber dari pola pikir masyarakat. Ketika perempuan mendapat batasan dalam berekspresi, ketika penilaian terhadap tubuh mereka lebih besar daripada suara mereka, maka ruang digital pun menjadi medan tempur baru yang sama tidak amannya.
Perundungan daring terhadap perempuan bukanlah “sekadar komentar jahat”. Ia adalah kekerasan yang menggerogoti harga diri, menyebarkan rasa takut, dan membungkam suara-suara perempuan di ruang publik. Dalam dunia yang semakin digital, kita harus berani mengubah pola “dari diam menjadi peduli, dari mengabaikan menjadi bertindak.” Karena pada akhirnya, setiap perempuan berhak merasa aman dan dihargai, baik di dunia nyata maupun di layar ponsel mereka.[]